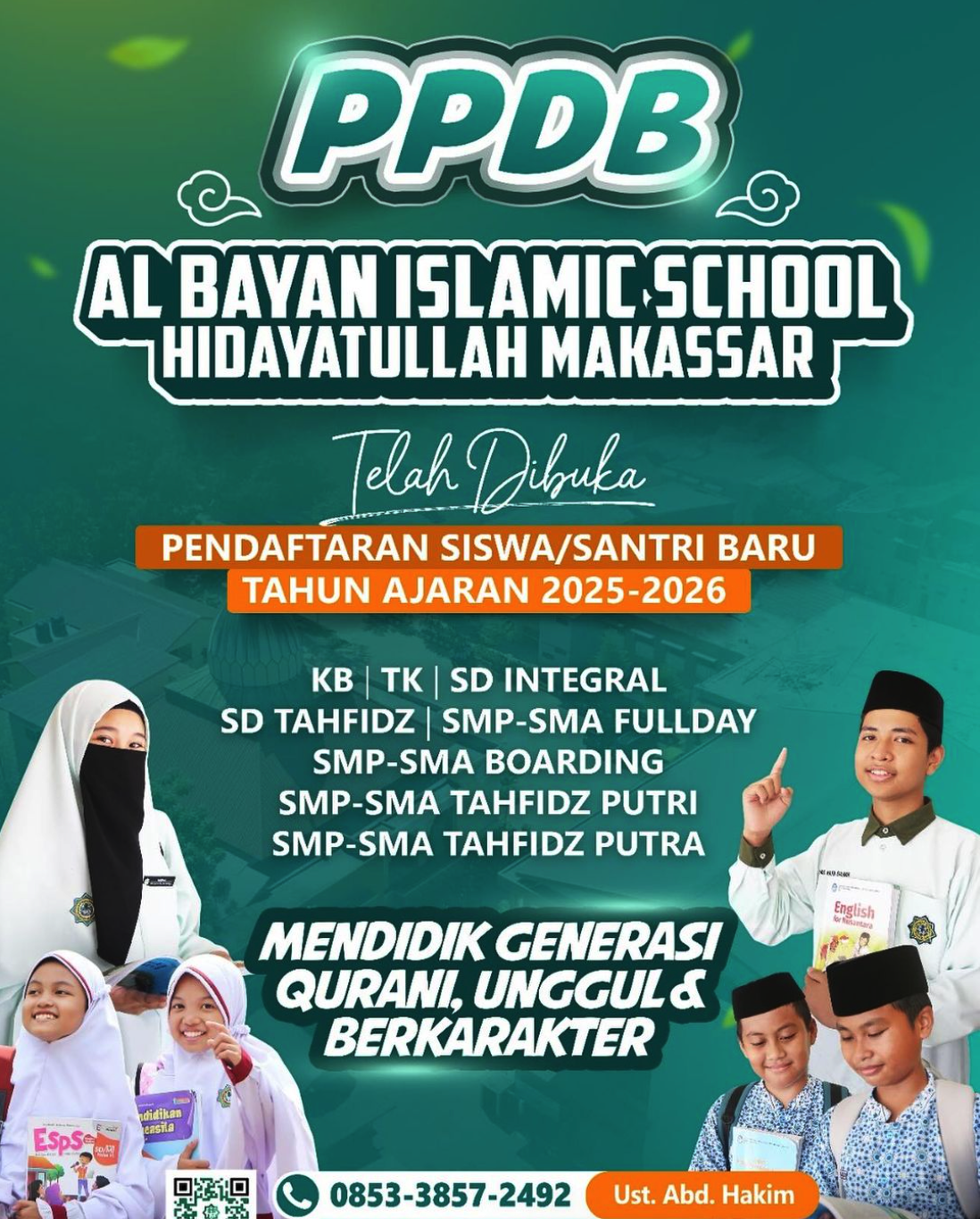Oleh: Irfan Yahya*
SESI ngopi pagi Ahad ini, duduk di tepi kolam rumah sambil menyimak video singkat sang “menteri koboy” Pak Purbaya, menghadirkan momen reflektif. Ketika ditanya wartawan tentang optimisme terhadap sistem perekonomian, ia menjawab dengan gaya khasnya, blak-blakan dan to the point . Ia menyebut bahwa respon, perilaku, dan sikap terhadap sistem perubahan dapat dibaca melalui dua kerangka analisis: statistik behavioral dan behavior sistem. Dari sanalah, ia menjelaskan bagaimana rekayasa sosial dan ekonomi dapat diarahkan untuk mencapai target tertentu. Potongan video itu nampak biasa saja, tetapi bagi penulis justru ini membuka ruang reflektif yang lebih luas: mungkinkah wajah sebuah gerakan sosial—termasuk gerakan dakwah dan tarbiyah—dapat ditelisik melalui dua cermin analitis tersebut?
Mengajukan pertanyaan ini penting karena gerakan sosial keagamaan kerap menghadapi dilema epistemologis. Di satu sisi, ia harus berpijak pada nilai-nilai transendental yang menjadi ruh perjuangan. Di sisi lain, ia dituntut untuk menghadirkan tata kelola yang profesional, terukur, dan adaptif terhadap zaman. Tanpa pijakan nilai, gerakan akan kehilangan identitasnya; tanpa tata kelola, gerakan akan kehilangan efektivitasnya. Di sinilah dua cermin analisis—statistik behavioral dan behavior sistem—menawarkan perspektif yang saling melengkapi.
Pendekatan statistik behavioral berangkat dari asumsi bahwa perilaku manusia dapat dipetakan secara kuantitatif. Pendekatakan ini menyoroti sejauh mana kader disiplin menjalankan GNH, sejauh mana keseriusan terlibat dalam kegiatan halaqah, seberapa sering jamaah berpartisipasi dalam program sosial, atau sejauh mana efektivitas pendidikan berbasis pondok terlihat dalam capaian nyata. Data ini tentu akan tersuguh apa adanya, tetapi justru itulah yang menjadikannya penting: ia menghadirkan cermin obyektif yang tidak bisa ditutupi oleh retorika. Misalnya, jika partisipasi kader menurun, maka realitas itu harus diakui, bukan disembunyikan di balik klaim keberhasilan.
Namun, statistik hanya memberi tahu apa yang terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi, dan apalagi bagaimana memperbaikinya. Di sinilah behavior sistem mengambil peran. Pendekatan ini melihat perilaku manusia tidak sebagai fakta terpisah, melainkan sebagai hasil interaksi dalam suatu sistem. Struktur organisasi, kultur kelembagaan, pola kepemimpinan, dan tata kelola sumber daya insani semuanya berkontribusi dalam membentuk perilaku kader. Dengan kata lain, rendahnya partisipasi kader bukan semata kesalahan individu, melainkan juga cerminan dari desain sistem yang mungkin tidak memberi ruang partisipasi yang relevan atau bermakna.
Perpaduan kedua cermin ini membuka ruang analisis yang lebih utuh. Statistik behavioral menyediakan peta lapangan yang faktual, sementara behavior sistem menawarkan kerangka desain untuk merumuskan solusi. Tanpa statistik, sistem hanya bergerak dalam ruang ide tanpa pijakan realitas. Tanpa sistem, statistik hanya menjadi tumpukan angka tanpa arah. Dengan memadukan keduanya, sebuah gerakan dapat membaca dirinya secara jernih sekaligus merancang langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.
Relevansi pendekatan ini semakin tampak ketika gerakan memasuki era transisi generasi. Generasi Z, yang kini mulai mengisi gelanggang dakwah, tumbuh dalam ekosistem digital dengan logika interaksi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Statistik dapat merekam pola partisipasi mereka—berapa banyak yang hadir di kegiatan offline, berapa banyak yang aktif di kanal dakwah digital, atau seberapa besar keterlibatan mereka dalam program sosial. Namun sistemlah yang dapat menjawab pertanyaan kritis: apakah pola kaderisasi sudah kompatibel dengan karakter mereka? Apakah tata kelola organisasi menyediakan ruang bagi ekspresi digital dan kreativitas mereka? Apakah manhaj mampu diterjemahkan dalam bahasa yang sesuai dengan habitus generasi ini tanpa kehilangan substansi?
Clue tsawabit dan mutagayyirat yang mengemuka saat sosialisasi Badan Pekrja Munas bulan di Makassar menjadi relevan. Statistik membantu mendeteksi celah partisipasi atau kelemahan dalam internalisasi nilai, sementara sistem membantu membedakan mana aspek yang bersifat prinsipil (tsawabit) dan mana yang bisa diubah (mutagayyirat). Misalnya, sistem halaqah adalah tsawabit karena ia berfungsi sebagai instrumen tarbiyah ruhiyah. Tetapi metode penyampaiannya—apakah dengan tatap muka, daring, atau hybrid—adalah mutagayyirat yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Statistik memberi tahu apakah halaqah berjalan efektif, sistem membantu merancang ulang formatnya agar relevan. Dengan begitu, kritik tidak berhenti pada gejala, melainkan diarahkan pada solusi yang konstruktif.
Lebih jauh, integrasi dua cermin ini menjaga keseimbangan antara orientasi profetik dan profesional. Orientasi profetik memastikan bahwa statistik dan sistem tidak kehilangan arah nilai: semua perhitungan dan desain dimaksudkan untuk meneguhkan iman, akhlak, dan misi dakwah. Sementara itu, profesionalisme memastikan bahwa orientasi profetik tidak berhenti sebagai jargon moral, melainkan diwujudkan dalam tata kelola yang terukur, adaptif, dan efektif. Tanpa profesionalisme, orientasi profetik berisiko menjadi retorika yang tidak pernah mengakar. Sebaliknya, tanpa orientasi profetik, profesionalisme dapat tergelincir menjadi teknokratisme pragmatis yang kehilangan ruh perjuangan.
Pendekatan ganda ini juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam nostalgia romantis terhadap masa lalu ataupun tergoda pada euforia modernitas yang serba cepat. Gerakan yang sehat adalah gerakan yang mampu membaca realitas dengan jujur, tetapi juga berani mendesain masa depan dengan visi. Ia tidak sekadar menjadi pengikut arus sejarah, melainkan pengendali arus yang menyalurkan energi sosial menuju tujuan peradaban. Dengan kata lain, statistik memberi kesadaran faktual, sistem memberi kesadaran strategis. Keduanya adalah syarat bagi transformasi yang berkelanjutan.
Maka tantangan kita adalah memastikan bahwa para pelaku—kader, aktivis, murabbi, dan jamaah—benar-benar mengalami transformasi, bukan hanya mengulang pola lama. Statistik behavioral memberi kita peta tentang apa yang sudah berjalan, behavior sistem memberi kita desain untuk perubahan. Jika keduanya dijalankan dengan sadar, gerakan ini akan tetap on the track: teguh pada nilai, adaptif pada zaman, dan selalu relevan dalam misi membangun peradaban. Wallahualam.
*Dr. Irfan Yahya, Sosiolog, Aktivis Hidayatullah