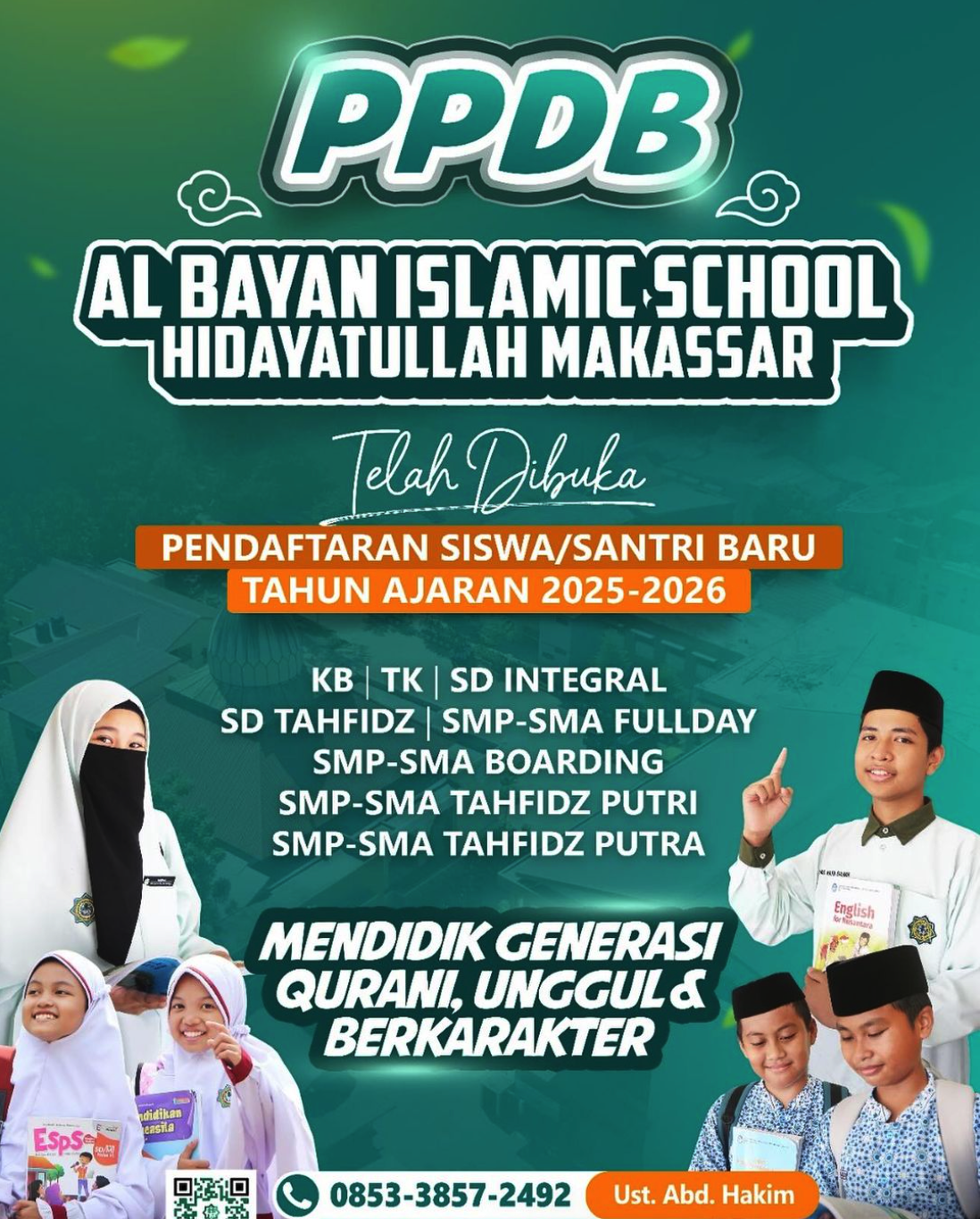Oleh: Irfan Yahya
Ada momen tertentu ketika refleksi pribadi bertemu dengan kebutuhan institusional untuk menuliskan apa yang dirasa-rasai. Dari arena acara Sosialisasi Badan Pekerja Munas VI Hidayatullah di Makassar (Ahad 7/9/2025), dengan sejumlah rancangan kebijakan strategis dan perubahan PDO yang sedang didiskusikan, saya menulis catatan pinggir ini sebagai bentuk keterpanggilan moral sebagai seorang kader aktivis lembaga perjuangan ini.
Catatan ini bukan untuk membela tanpa syarat, bukan pula untuk menghakimi dari luar, melainkan untuk mengukuhkan satu hal sederhana namun mendasar, bahwa permasalahan yang dihadapi kini pada intinya adalah soal transmisi manhaj, bukan masalah pada hal-hal substansi dan filosofis. Grand design telah menempatkan gerak organisasi pada peta yang panjang, di mana pada titik ini yang diperlukan adalah ketepatan cara mewariskan, bukan pada urusan mengganti peta.
Manhaj yang selama ini membimbing perjalanan kolektif jamaah bukanlah retorika kosong. Dalam kerangka yang secara historis dan teoritik dirumuskan dalam pola dasar yang berangkat dari urutan lima surat pertama, organisasi telah sukses merumuskan peradaban Islam sebagai sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Yaitu manifestasi iman dalam kehidupan sehari-hari.
Pendefenisian ini bukan sekadar slogan. Ia menjadi tolok ukur epistemik untuk menilai apakah pergerakan lembaga benar-benar menginternalisasi nilai-nilai sistematika wahyu menjadi praktik. Atau baru sekadar menempelkan label religius pada praktik yang berorientasi pragmatis semata.
Prinsip Sistematika Wahyu mengajarkan urutan transformasi, mulai dari pembentukan kesadaran tauhid hingga pembinaan ruhiyah, dari perluasan dakwah keluar hingga tujuan Islam kaffah, merupakan sebuah rangka yang menuntut kesabaran lintas generasi, instrumen pendidikan yang terstruktur, serta ukuran keberhasilan yang berbeda dari logika output ekonomi semata.
Di sisi lain, wajar jika kita memandang kondisi organisasi sekarang dengan mata kritis. Sebab memang banyak hal administratif, struktural, dan kapasitas yang memang perlu pembenahan. Namun yang patut disyukuri, dan inilah aset epistemik yang menjadikan perjuangan ini bertahan, adalah keberadaan tsawabit, yakni substansi yang paten, yang secara tegas menempatkan konsep kepemimpinan imamah jamaah dan sistem syuro sebagai fondasi kolektif.
Sementara itu, pada ranah teknis dan taktis, yang sifatnya mutaghayyirat, organisasi terus berbenah dalam menunjukkan kapasitas yang adaptif. Sebut saja misalnya: pola pendidikan, metode pengaderan, struktur kelembagaan, dan pemanfaatan instrumen teknologi yang terus disesuaikan agar relevan dengan konteks zamannya.
Transformasi dan rejuvenasi yang diusulkan dalam rancangan arah kebijakan strategis dan PDO sangat jelas menempatkan keseimbangan antara menjaga substansi dan meremajakan strategi sebagai prioritas.
Memahami proses internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi yang menjadi bagian dari dinamikanya memberi kita kerangka evaluasi yang lebih adil. Internalisasi berarti nilai menjadi disposisi, objektivasi berarti nilai itu terwujud dalam struktur organisasi, dan eksternalisasi berarti nilai itu tampil dalam karya nyata berupa pesantren, institusi pendidikan, amal usaha, dakwah ke masyarakat, yang bersama-sama membentuk miniatur peradaban berbasis kampus/pondok.
Kegagalan yang sering dikritik bukanlah soal ketiadaan konsep. Tapi ia lebih kerap berakar pada kebocoran proses ini, di mana kualitas pendidikan kader, standardisasi murabbi, atau mekanisme monitoring dan evaluasi belum konsisten sehingga hasilnya belum menyebar merata ke generasi pelanjut. Membaca dinamika ini dengan lensa sosiologi pengetahuan (Epistemologi dalam dunia Filsafat) berarti menuntut intervensi pada perangkat tarbiyah, bukan pembongkaran identitas.
Masa kini menuntut perhatian ekstra pada aspek transmisi. Sebab generasi yang hidup di era digital memiliki kebiasaan komunikasi, ritme perhatian spesifik, dan cara belajar yang berbeda. Mereka bukan “generasi digital” sebagai label esensial. Yang lebih tepat dikatakan: mereka adalah generasi yang hidup di era digital, mengalir dalam kultur multi-kanal, dipengaruhi oleh hukum dan logika algoritma, menuntut otentisitas serta fleksibilitas.
Tantangan kita bukan merumuskan kembali jati diri. Justru tantangan praktisnya adalah merancang medium dan ritme pembinaan yang resonan tanpa menukar substansi dengan kemasan. Halaqah hybrid, inkubator sosial yang mengaitkan proyek ekonomi kader dengan mengkapitalisasi pontensi jaringan yang ada tetap dalam bingkai manhaji, kurikulum yang menyisipkan literasi digital dan etika siber, serta skema evaluasi yang menilai kualitas internalisasi, semua ini adalah komponen konkret dari strategi transmisi yang efektif.
Pada capaian ini sesuatu yang wajar dan penting menegaskan bahwa profetik dan profesional bukanlah dua ranah yang bisa berdiri sendiri. Keduanya mesti dipandang sebagai rangkaian yang saling melengkapi. Profetik memberi orientasi moral, menjaga integritas visi, dan menyalakan ruh tarbiyah. Sementara profesional memberi metode, tata kelola, dan akuntabilitas yang memungkinkan visi itu terwujud secara efektif.
Profetik tanpa mekanisme yang rapi berisiko menjadi moralitas retoris. Dan profesional tanpa pijakan profetik berbahaya karena bisa mengarahkan organisasi ke pragmatisme yang kehilangan ruh. Oleh karena itu rancangan kebijakan strategis yang mengusung integrasi profetik-profesional adalah langkah konseptual yang logis yang kini mesti diterjemahkan ke dalam pelatihan murabbi berbasis pedagogi digital, tata kelola ekonomi yang transparan, dan sistem monitoring yang partisipatif.
Praktik yang konkret haruslah terukur. Pertama, standardisasi murabbi dan sertifikasi instruktur bukanlah teknokrasi kering, melainkan cara memastikan bahwa proses transmisi nilai memiliki medium pengajar yang benar-benar kompeten, memahami manhaj, sekaligus mampu membaca konteks generasi kini.
Kedua, pengelolaan kampus sebagai etalase peradaban perlu diarahkan menjadi laboratorium praktik sebagai ruang tempat menguji dan melahirkan berbagai karya nyata. Seperti proyek ekonomi sosial, riset dan publikasi akademik, serta ekspresi seni budaya yang bernafaskan nilai profetik.
Ketiga, digitalisasi, baik dalam bentuk pendataan alumni, pembangunan platform ekonomi jamaah, maupun pengembangan kurikulum hybrid, harus dirancang untuk memperkuat objektivasi nilai, bukan sekadar mempermudah distribusi informasi.
Keempat, indikator evaluasi juga mesti diperbarui. Bukan lagi berhenti pada kuantitas kegiatan, tetapi bergerak pada kualitas internalisasi dengan standar ukuran yang adil dan proporsional (efel to efel), yang menilai kedalaman iman sebagaimana termanifestasi dalam tindakan keseharian.
Adalah penting pula menyatukan rasa syukur dan semangat jihad tandang ke gelanggang dakwah. Mengakui kekurangan internal dan eksternal bukan berarti memandang gerakan sebagai sebuah kegagalan. Sebaliknya, mengakui jejak kejayaan yang telah ada yaitu jejak yang lahir dari praksis gerakan nawafil, pembangunan pesantren, pendirian sekolah integral, dan jaringan pengabdian yang tumbuh, adalah landasan untuk bergerak lebih berani.
Warisan (legacy) para pendiri, termasuk otoritas intelektual yang ditinggalkan oleh generasi awal, mestinya memberi inspirasi praktis, di mana Ustad Abdullah Said rahimahullah telah mewariskan kader-kader yang mampu menerjemahkan manhaj ke dalam praktis. Sehingga tugas generasi sekarang adalah memastikan warisan itu benar-benar terangkai ke dalam jaringan generasi Z yang akan mengambil alih kemudi nahkoda di masa kini dan datang, sesuai kadar kemampuan masing-masing (ma-staṭho’tum).
Transformasi, rejuvenasi, dan perjuangan adalah istilah yang hidup dalam dinamika organisasi. Ketiganya bukan sekadar jargon, melainkan refleksi dari proses yang terus berulang dalam perjalanan lembaga perjuangan ini. Kendatipun perlu ditegaskan bahwa yang kita perlukan sekarang adalah transmisi yang utuh, yaitu transmisi yang memastikan bahwa nilai (jati diri) dan kultur (GNH) ikut terwariskan tanpa retak.
Rejuvenasi yang sehat bukanlah sekedar urusan umur semata, melainkan memperbarui cara pewarisan agar relevan. Dengan pendekatan itu, beberapa perubahan dalam PDO dapat dinilai menjadi instrumen untuk menjaga kemurnian manhaj sekaligus memberikan ruang bagi manajemen yang lebih adaptif. Implementasi kebijakan strategis yang sedang disosialisasikan menunjukkan arah itu, dan kini giliran kader muda untuk mengisi ruang-ruang praktik tersebut.
Akhirnya, melalui catatan pinggir ini, saya memberi usulan sederhana namun mendesak. Pertama, jadikan setiap langkah kita, dari halaqah, GNH, pengembangan kampus, hingga pengelolaan ekonomi berbasis jaringan, sebagai upaya kolektif untuk menjadikan manhaj hidup dalam denyut keseharian generasi yang hidup di era digital. Jangan sampai perdebatan soal struktur organisasi menutupi urgensi yang lebih mendasar yaitu murabbi yang berkualitas, rancangan kurikulum yang relevan dengan zaman, dan menyediakan platform yang memungkinkan kader benar-benar mempraktikkan nilai dalam kehidupan nyata.
Bila setiap kader melakukan bagian kecilnya dengan konsistensi dan kesungguhan sesuai kemampuan, maka skala besar perubahan akan mengikuti. Transisi perlu, transformasi diperlukan, namun yang utama adalah transmisi harus berhasil. Pada kondisi kesadarann ini, lima puluh tahun bukanlah penghujung, melainkan landasan untuk menapaki separuh abad berikutnya dengan keyakinan bahwa peradaban Islam bukan sekadar wacana, melainkan denyut yang hidup dalam setiap aspek kehidupan.
Catatan pinggir ini dihadirkan untuk menjadi pengingat bahwa mewariskan manhaj adalah kerja hati, kepala, dan tangan, yatu sesuatu yang mesti dilakukan bersama, dengan kesiapan untuk belajar dan memperbaiki sampai tujuan peradaban itu benar-benar hidup di tangan generasi pelanjut.
Allahu Akbar. Wallahualam.
*Dr. Irfan Yahya, Sosiolog dan Aktivis Hidayatullah.